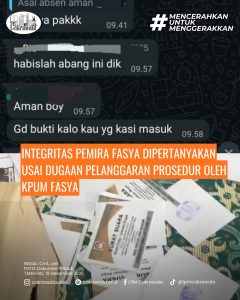RUU KUHAP Pembungkaman Suara Kampus dan Jalanan

Sebagai mahasiswa kita diajarkan bahwa hukum adalah pelindung warga, bukan untuk membatasi. Tapi ada sesuatu yang mengusik saat membaca dan mengikuti pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Regulasi yang katanya lahir dari semangat pembaruan justru meninggalkan pertanyaan mengenai hukum yang sebenarnya ingin apa: melindungi rakyat, atau menata panggung baru bagi kekuasaan?
RUU KUHAP hadir dengan ramah dengan menjunjung perlindungan hak korban, mengakui kelompok rentan, dan mengusung jargon keadilan restoratif. Tetapi sejarah hukum mengajarkan kita satu hal, pasal bisa tersusun rapi dan meyakinkan, tapi kekuasaan tidak selalu jujur. Hukum bukan hanya tentang apa yang tertulis, melainkan apa yang memungkinkan dan apa yang dapat disalahgunakan.
Revisi KUHAP yang dibahas sejak awal 2023 dan disahkan pada Selasa (18/11/2025) seharusnya menjadi tonggak sejarah hukum pidana yang lebih manusiawi. Tetapi alih-alih menenangkan, ia justru memantik kegelisahan. Bukan karena masyarakat menolak pembaruan, tetapi karena pembaruan itu terasa condong bukan pada rakyat, melainkan pada negara. Terlalu banyak ruang abu-abu, terlalu banyak celah kuasa, dan terlalu sedikit jaminan akuntabilitas.
Di balik narasi perlindungan, muncul ironi yang sulit diabaikan, dalam KUHAP baru memberikan wewenang penyadapan lebih longgar, bahkan sebelum izin hakim diperoleh dan izinnya boleh menyusul belakangan. Ini bukan hanya soal efektivitas penyidikan, tetapi soal logika kekuasaan yang ingin melihat tanpa terpergoki, mengawasi tanpa dimintai pertanggungjawaban. Privasi masyarakat perlahan berubah bukan lagi menjadi hak, tapi fasilitas yang bisa dicabut demi ‘kepentingan penyidikan’.
Tidak berhenti di situ. Perpanjangan penahanan yang berlapis mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim memperlihatkan wajah hukum yang kian represif. Seseorang bisa mendekam dalam tahanan selama berbulan-bulan tanpa kepastian bersalah, karena hukum kini memberi ruang bagi negara untuk menahan lebih dulu, membuktikan belakangan. Prinsip praduga tak bersalah bergeser menjadi praduga ketidakberdayaan masyarakat di hadapan kewenangan.
Keresahan ini bergema di kampus dan ruang diskusi publik. Kami sebagai mahasiswa memahami bahwa hukum adalah pagar demokrasi. Tapi pagar itu kini tampak condong ke arah yang berbeda, bukan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi memberi kekuasaan ruang untuk melampaui kontrol warga. Di jalanan, Spanduk-spanduk sederhana dengan tulisan “tolak rezim tanpa kontrol” berbicara lebih jujur daripada naskah akademik pemerintah yang gemar berbicara tentang ‘modernisasi sistem hukum’.
Masyarakat tidak takut pada hukum. Yang mereka takuti adalah hukum ketika ia diubah menjadi sarung tangan kekuasaan. Pertanyaannya bukan lagi apa isi pasal, tapi ke mana negara ingin menbawa hukum? Apakah hukum akan berdiri di sisi rakyat, atau berdiri tegap di balik podium kekuasaan?
Sebagai mahasiswa, kami diajarkn untuk berpikir kritis. Dan dengan rasa kritis itu membuat kami justru mempertanyakan tentang bagaimana mungkin hukum membicarakan perlindungan tetapi di satu sisi memberi celah bagi pelanggaran? Bagaimana bisa negara berbicara tentang akuntabilitas, tapi mengunci ruang pengawasan publik? Jika hukum digunakan untuk mengunci ruang kritik, maka hukum sedang melayani kekuasaan, bukan menjaga keadilan.
Negara mulai melihat warganya, tetapi siapa yang menjamin warga masih dapat melihat negara?
Bukannya menolak pembaruan hukum, justru karena kita percaya pada hukum. Hukum harus memberi rasa aman, bukan rasa diawasi. Sebab hukum bukan sekadar teks dalam lembar negara melainkan napas bagi demokrasi, rumah bagi kebebasan, dan perlindungan terakhir bagi masyarakat.
Jika undang-undang ini ingin dipercaya, ia tidak hanya perlu mengatur, tetapi juga harus membuktikan bahwa kekuasaan bisa dibatasi agar masyarakat bisa tetap merasa aman.
Dan di titik ini, suara penolakan bukan lagi soal sekedar sikap politik, melainkan menjadi panggilan moral. Sebab hukum tidak hanya membutuhkan kepatuhan. Ia butuh pengawasan, keberanian untuk bertanya, dan tekad untuk menjaga kekuasaan agar tidak tumbuh lebih cepat dari akuntabilitasnya.
(Elf) / (Cmt)