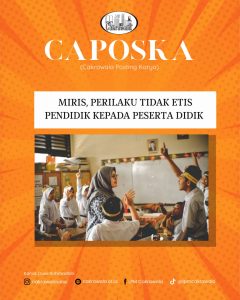Hafal Ayat, Buta Makna Ayah: Ketika Iman Laki-laki Hanya Sampai di Tenggorokan, Bukan di Hati Anaknya
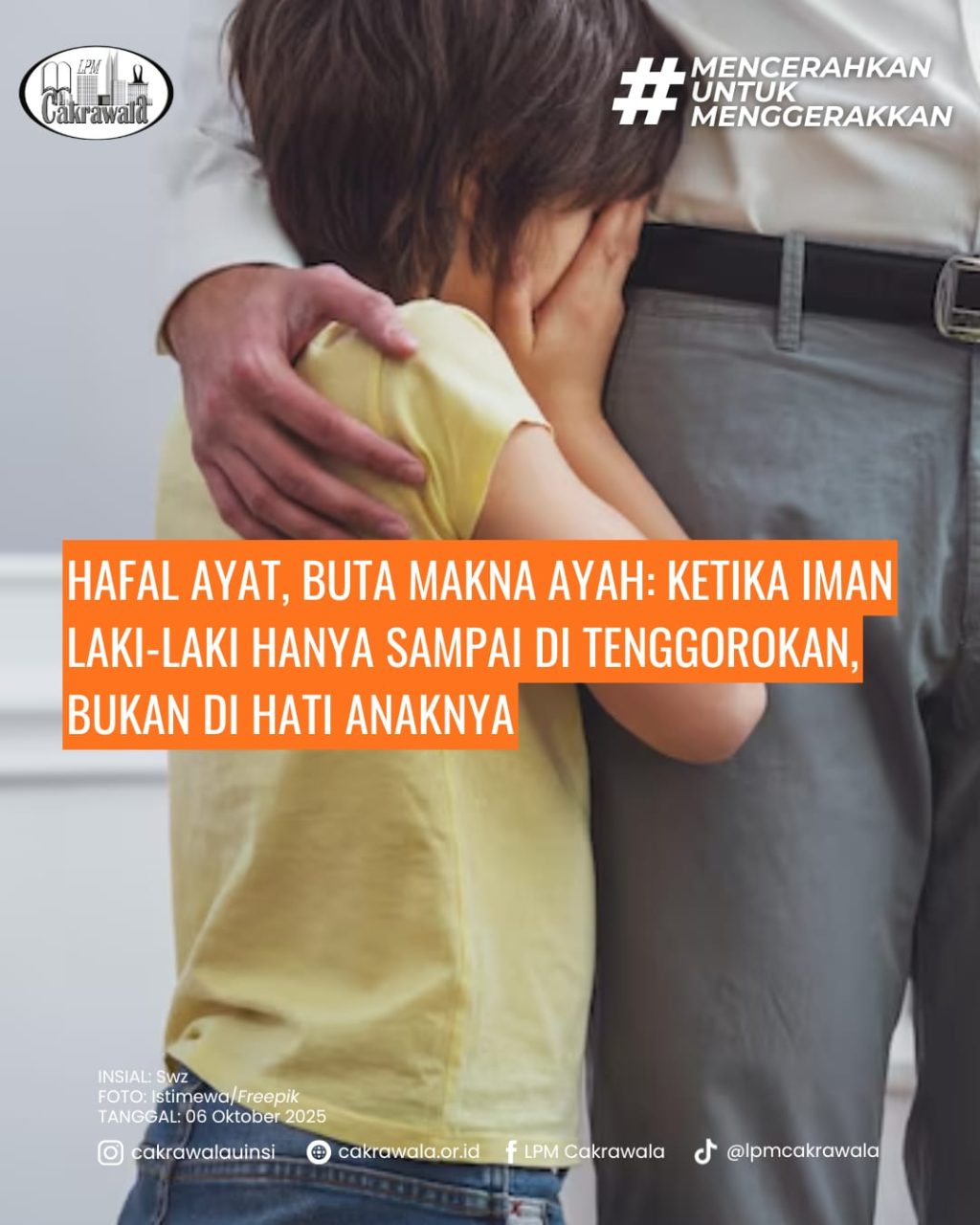
Fenomena fatherless— ketiadaan sosok ayah secara emosional meski ia hadir secara fisik, telah lama menjadi luka sosial yang sepi diucapkan. Ironisnya, sebagian luka justru datang dari tangan mereka yang mengaku paling mengerti tentang qawwam, ilmu kepemimpinan laki-laki dalam Islam. Laki-laki yang hafal ayat, tapi tak lagi hafal makna kasih.
Banyak di antara mereka berdiri di mimbar, menyebut diri imam keluarga, tapi di rumah hanya meninggalkan jejak marah, bukan teladan. Mereka mengutip ayat tentang kepemimpinan suami, namun menanggalkan ayat tentang kelembutan, keadilan, dan kasih sayang (rahmah). Mereka adalah pemimpin di luar rumah, namun bagi anak dan istri, mereka tak lebih dari penghuni asing. Padahal, Islam menempatkan peran ayah bukan hanya sebagai penyedia, tetapi pendidik yang membangun akhlak dan perasaan aman bagi anak dan istri.
Sering kali, pembenaran datang dari kalimat yang tampak mulia seperti, “Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.” Kalimat itu benar, tapi tafsirnya sering keliru. Karena jika ibu adalah madrasah, maka ayah seharusnya menjadi kepala sekolah yang membangun sistem nilainya. Namun yang terjadi, tanggung jawab pendidikan anak seolah selesai di tangan ibu, sementara ayah merasa cukup dengan status pencari nafkah. Dari situlah akar fatherless tumbuh— ketika laki-laki melepaskan peran batin, lalu berlindung di balik jargon patriarki dan dalil tanggung jawab finansial.
Padahal Islam tidak pernah memisahkan kasih dan kuasa. Rasulullah bukan hanya pemimpin ummat, tetapi juga ayah yang hadir penuh cinta. Ia menambal sandalnya sendiri, mencium cucunya tanpa malu, memanggil istrinya dengan panggilan lembut. Tapi hari ini, sebagian laki-laki yang mengaku meneladaninya justru menjadikan agama sebagai pagar bagi ego, bukan cermin bagi akhlak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2023 tercatatat lebih 25% anak di Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan emosional ayah, meski ayah masih tinggal di satu atap. Data yang sama menunjukkan 74% kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa dan minimnya komunikasi efektif antar anggota keluarga.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa fatherless bukan hanya krisis keluarga, tapi juga krisis kepemimpinan. Agama sering dipahami sebagai struktur kuasa, bukan ruang kasih sayang. Dan ketika agama kehilangan rasa, patriaki menjelma jadi pelajaran pertama anak tentang ketakutan.
Maka jika kita ingin menghentikan rantai fatherless, pendidikan agama harus direvisi dari dalam: bukan sekadar mengajarkan hafalan ayat, tapi menanamkan makna. Bukan meneguhkan siapa pemimpin, tapi bagaimana memimpin dengan cinta. Dan mungkin, dunia ini mulai kehilangan arah bukan karena ibu gagal mendidik, tetapi karena terlalu banyak ayah yang absen— secara fisik, emosional, dan spiritual.
Karena fatherless bukan sekadar ketiadaan ayah, tetapi gagalnya laki-laki memahami dirinya sebagai rahmat. Dan mungkin, dunia ini mulai rusak bukan karena laki-laki kurang beragama, tapi karena terlalu banyak yang beragama tanpa belajar menjadi manusia.
(Swz) / (Cmt)