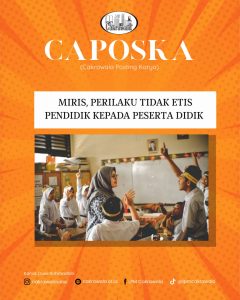Polemik Pembangunan Rumah Ibadah Bak Kisah Cinta Yang Tak Ada Akhir

Setiap kali kita bicara tentang pembangunan rumah ibadah di Indonesia, rasanya seperti memutar lagu lama yang nadanya tak pernah berubah. Mengalun sendu, penuh ketegangan,
dan berakhir sumbang. Seolah-olah negara ini belum cukup belajar dari puluhan kasus serupa yang meletup dari Sabang hingga Merauke. Episode terbaru dari drama klasik ini kembali diputar di panggung kehormatan Sungai Keledang, Samarinda.
Gereja Toraja yang hendak didirikan di kawasan itu belum mengantongi izin dari pemerintah daerah. Begitu setidaknya isu yang berkembang. Namun fakta yang lebih tak terbantahkan adalah fenomena penolakan yang terjadi justru dilangsungkan lewat pemasangan spanduk besar— sebuah tindakan kolektif warga yang tak sekadar menyuarakan aspirasi, tetapi berpotensi membentuk opini publik yang represif dan mengarah pada penghakiman sosial terhadap satu golongan tertentu.
Lebih ironis lagi, di tengah polemik ini, muncul pula gejala berbahaya yang patut dicermati dan diwaspadai, yakni penyematan predikat moral atau stigma sosial terhadap etnis tertentu. Ini adalah kekeliruan logika yang sangat kasar, sebuah _logical fallacy_ yang mengaburkan akar persoalan sebenarnya dan akan menggiring opini publik pada prasangka berbasis etnis. Apa kaitannya antara pernyataan sikap masyarakat setempat dengan karakter etnis?
Tidak ada. Tapi celah ketegangan semacam ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana, menanamkan stigma, dan menyulut emosi kolektif. Kasar dan sangat tidak bermoral.
Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya mencederai martabat suatu kelompok, tetapi juga merusak struktur sosial kita yang majemuk. kemajemukan yang dipelihara jauh sebelum negara yang katanya berhukum ini didirikan.
Mari kita kembali mengambil jalan yang lurus. Dalam negara hukum seperti Indonesia, tak ada ruang pembenaran bagi tindakan main hakim sendiri, apalagi atas nama mayoritas.
Bahwa rumah ibadah itu belum memiliki izin resmi dari pemerintah setempat menjadi satu kebenaran yang diyakini masyarakat setempat, tapi bukankah justru karena itulah mekanisme penyelesaian perlu dikembalikan kepada aparat dan institusi yang berwenang? Ketika warga merasa berhak menjadi penentu sah tidaknya suatu rumah ibadah berdiri, maka kita sedang menyaksikan kemunduran fungsi negara sebagai satu instrumen penjamin keadilan.
Sebagian pihak kerap berdalih bahwa penolakan seperti ini adalah bentuk ‘aspirasi warga’. Tapi di balik eufemisme itu, sering tersembunyi ketakutan yang tak berdasar, prasangka lama yang diwariskan, dan minimnya literasi hukum maupun keagamaan. Seandainya kita benar-benar membaca dan memahami guna mencerdaskan diri terkait Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kita akan tahu bahwa negara telah merumuskan prosedur yang adil dan terukur, yang dimana ada syarat administratif, ada verifikasi, ada dialog lintas umat, dan ada forum penyelesaian sengketa. Semua itu dirancang untuk mencegah konflik horizontal seperti yang kini terjadi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seolah ada semacam budaya vigilante yang dibiarkan tumbuh dan berkembang dimana warga bisa mengambil alih peran negara, atas nama harmoni yang definisinya pun dibuat sepihak.
Apa yang kita hadapi bukan sekadar perkara izin atau tidak izin. Ini adalah soal cara kita memperlakukan minoritas, soal bagaimana negara hadir atau absen di tengah pusaran perbedaan, dan lebih dari itu: soal bagaimana kita memahami arti sesungguhnya dari kemanusiaan dan moralitas. Jika pendirian rumah ibadah non-Muslim selalu tersandung pada dinamika sosial-politik, lantas bagaimana kita bisa membangun masyarakat plural yang sehat? Apakah rumah ibadah hanya boleh berdiri jika mayoritas menyetujui? Bila iya, maka prinsip-prinsip konstitusional kita runtuh di hadapan dominasi suara terbanyak.
Kita harus berani berkata jujur bahwasannya tidak setiap penolakan mencerminkan kearifan lokal. Kadang ia hanyalah manifestasi dari intoleransi yang diwariskan dan dibungkus secara santun. Dan jika negara terus membiarkan praktik ini, maka kita sedang menciptakan hal berbahaya: bahwa hak asasi bisa ditawar oleh opini massa.
Polemik seperti ini seharusnya menjadi cermin. Ia merefleksikan masih jauhnya jarak antara semangat pluralisme yang digembar-gemborkan dengan realitas sosial di lapangan. Solusinya bukan represi, apalagi pembiaran. Solusinya adalah penegakan hukum, pencerdasan hukum, edukasi keagamaan lintas komunitas, dan yang paling penting adalah kehadiran negara yang tegas, adil, dan tidak gamang. Sampai itu terjadi, lagu lama ini akan terus dinyanyikan. Kita hanya berganti aktor, tapi naskahnya tetap sama. Kisah cinta tak berbalas antara konstitusi dan kenyataan. Dan kisah ini tak akan menemukan akhirnya, selama negara terus membiarkan warga memegang kendali atas hak dasar dari tiap warga negara yang seharusnya tak perlu diperdebatkan, yakni hak untuk beribadah.
Penulis: Bondan Tri Atmaja